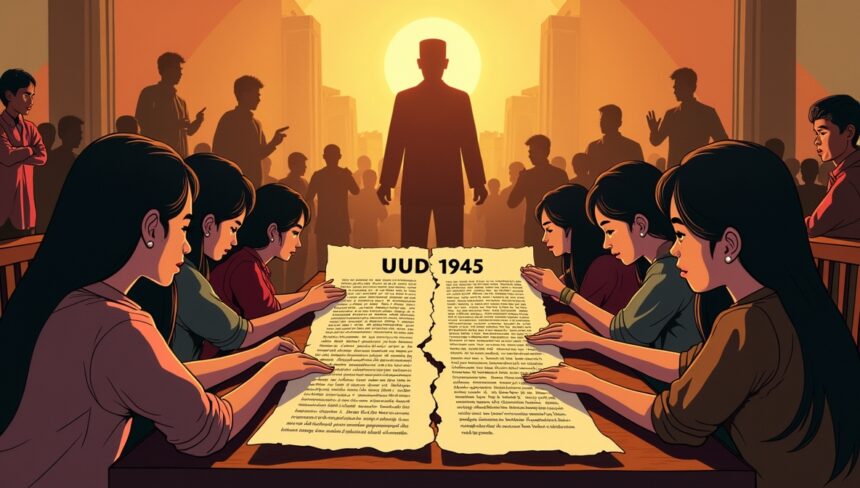Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Perdebatan mengenai Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia 1945 (UUD NRI 1945) selalu diiringi kecemasan. Trauma sejarah masa lalu, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berubah menjadi alat kekuasaan dan konstitusi dipakai untuk melegitimasi dominasi elite partai politik, membuat sebagian kalangan memilih sikap ekstra hati-hati, bahkan cenderung menutup pintu perubahan sama sekali. Kekhawatiran itu wajar. Namun, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi pembiaran terhadap kerusakan sistemik yang terus berlangsung.
Hari ini, masalah bangsa Indonesia bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana desain kekuasaan itu sendiri disusun. Ketika korupsi merajalela, keadilan timpang, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta lembaga-lembaga negara saling tumpang tindih dan kehilangan fungsi, persoalannya bukan lagi moral individu semata. Ia adalah krisis desain ketatanegaraan.
Trauma Sejarah Tidak Bisa Dijawab dengan Status Quo
Trauma masa lalu sering dijadikan alasan untuk menolak pembicaraan amandemen. Padahal, justru trauma itu menuntut jawaban yang lebih matang, bukan penghindaran. Menghindari koreksi konstitusi sama artinya dengan mewariskan sistem yang bermasalah kepada generasi berikutnya.
Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah menyampaikan kegelisahan yang sangat relevan dengan situasi ini. Dalam sebuah forum, ia berkata:
“Untuk teman-teman Fakultas Hukum, saya mohon dalam waktu tiga tahun ada buku dari anda semua. Ada tim peneliti. Gini lho seharusnya Indonesia secara konstitusi dan hukum. Kalau itu ada, besok anakmu tinggal memakai.”
Pernyataan ini bukan seruan emosional, melainkan tanggung jawab intelektual lintas generasi. Konstitusi bukan hanya alat kekuasaan hari ini, melainkan warisan peradaban. Jika hari ini kita gagal membenahinya, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung akibatnya.
Sekolah Negarawan dan Desain Kedaulatan Rakyat yang Baru
Berangkat dari kesadaran tersebut, Sekolah Negarawan menyusun sebuah rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 yang tidak mengulang kesalahan sejarah. Justru sebaliknya, rancangan ini secara sadar dibangun untuk menutup celah penyalahgunaan kekuasaan yang dulu pernah terjadi.
Dalam konsep Sekolah Negarawan, MPR tidak lagi dibentuk seperti masa lalu, yang anggotanya berasal dari DPR, utusan golongan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga mudah dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif. MPR versi baru dirancang sebagai representasi filosofis dan substantif kedaulatan rakyat, yang berasal dari empat unsur penjaga kedaulatan, yaitu:
- Kaum Intelektual (penjaga nalar dan kebijakan),
- Kaum Rohaniawan (penjaga moral dan etika),
- Kaum Budayawan dan Adat (penjaga identitas dan nilai Nusantara),
- TNI dan Polri (penjaga keamanan dan kedaulatan negara).
Rakyat ditempatkan sebagai pusat (pancer) dari keseluruhan struktur ini, bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan pemilik mutlak kedaulatan. Dengan desain seperti ini, MPR tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan penjaga arah negara, sekaligus pengimbang yang sah dan bermartabat terhadap pemerintah.
Presiden sebagai Pelaksana, Bukan Pemilik Kekuasaan
Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 juga menegaskan pemisahan yang sehat antara kedaulatan dan pemerintahan. Presiden ditempatkan secara tegas sebagai Kepala Pemerintahan, bukan pemilik kedaulatan tertinggi. Kekuasaan eksekutif dijalankan dalam kerangka pelayanan publik, dengan pengawasan yang kuat dan sistemik.
Dalam konteks ini, kritik Cak Nun kembali menemukan relevansinya. Ia pernah menyebut presiden sebagai “buruh lima tahun”, bukan dalam rangka merendahkan jabatan, melainkan untuk mengembalikan makna mandat demokrasi: bahwa presiden adalah pekerja rakyat, bukan majikan rakyat.
Amandemen sebagai Tindakan Bertanggung Jawab, Bukan Petualangan Politik
Amandemen Kelima UUD 1945 yang dirancang Sekolah Negarawan bukanlah langkah tergesa-gesa, apalagi petualangan politik. Ia adalah hasil refleksi filosofis, kajian historis, dan kehati-hatian konstitusional untuk memastikan kesalahan masa lalu tidak terulang, sekaligus kesalahan hari ini tidak diwariskan.
Menolak perubahan atas nama trauma sejarah justru berisiko melanggengkan kerusakan yang sama dalam bentuk berbeda. Sebaliknya, melakukan amandemen dengan desain yang jernih, partisipatif, dan berakar pada nilai Pancasila serta kebudayaan Nusantara adalah bentuk tanggung jawab moral kepada bangsa.
Konstitusi untuk Anak Cucu Bangsa
Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berani merdeka, tetapi bangsa yang berani mewariskan sistem yang adil dan sehat. Seruan Cak Nun agar konstitusi dirumuskan dengan sungguh-sungguh agar “besok anakmu tinggal memakai”, adalah panggilan etis bagi generasi hari ini.
Amandemen Kelima UUD NRI 1945 bukan tentang kepentingan politik sesaat. Ia adalah tentang menata ulang rumah besar bernama Indonesia, agar tidak lagi bocor di mana-mana, dan benar-benar mampu melindungi seluruh penghuninya.
Trauma sejarah harus diakui.
Namun masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan olehnya.